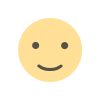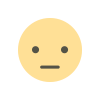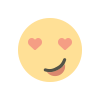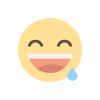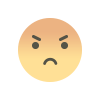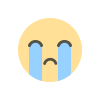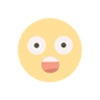Parpol, Politik Identitas dan Konsolidasi Demokrasi
Oleh: Boy Anugerah
Dalam konteks demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia, peran partai politik sangatlah penting sebagai pilar demokrasi yang menyelenggarakan fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, kaderisasi politik, komunikasi politik, hingga kandidasi politik pada Pemilu di berbagai jenjang, eksekutif dan legislatif. Dapat dikatakan bahwa partai politik menjadi saluran kunci dan pemegang tiket emas bagi warga negara yang hendak menjadi wakil rakyat di parlemen dan pimpinan nasional di berbagai level pemerintahan. Partai politik menjadi suprastruktur politik yang melakukan penggemblengan dan penyaringan terhadap siapa pun warga negara yang hendak berkontestasi pada politik elektoral.
PARA pendiri bangsa telah menyepakati bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dan sistem politik yang dianut dan dipraktikkan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Frasa demokrasi, meskipun tidak disebutkan secara lugas dalam konsensus dasar kebangsaan, akan tetapi menjadi ruh dan memiliki benang merah dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsensus dasar kebangsaan Indonesia.
Pada era pasca reformasi, konsolidasi demokrasi menjadi fase vital dalam dinamika demokratisasi yang dilalui oleh Indonesia. Fase ini merupakan sekuensi dari fase-fase sebelumnya yang sudah dilalui, yakni fase inisiasi demokrasi dan fase instalasi demokrasi. Fase konsolidasi demokrasi, yang oleh banyak pihak disebut sebagai transisi demokrasi, merupakan periode waktu yang menuntut segenap komponen bangsa untuk menyatukan cara pandang dalam berbangsa dan bernegara dengan meletakkan demokrasi sebagai orientasi bersama.
Pilar demokrasi
Dalam bahasa politik Juan J. Linz, pakar demokrasi dari Universitas Yale AS, konsolidasi demokrasi hanya dapat terwujud ketika demokrasi diposisikan sebagai the only game in town oleh semua pihak. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah menguatnya politik identitas pada Pemilu. Pemilu yang seyogianya menjadi ajang pesta demokrasi rakyat berubah wujud menjadi ajang pecah belah masyarakat oleh partai politik dan elit yang bertarung dengan menggunakan isu-isu berbasis SARA.
Sebagai contoh, Pilkada DKI Jakarta 2017. Rakyat Indonesia terbelah menjadi kelompok pro-pribumi versus pro-peranakan, serta kelompok religius yang berhadap-hadapan dengan kelompok nasionalis. Situasi ini tidak baik bagi kebhinnekaan. Proses pembentukan Indonesia sebagai sebuah bangsa adalah proses yang sangat mahal yang dibangun dengan keringat, darah dan air mata para pejuang. Ada tahapan panjang yang dilalui mulai dari tumbuhnya gerakan kemerdekaan pada 1908, terekatnya simpul persatuan melalui Sumpah Pemuda 1928, hingga proklamasi kemerdekaan. Penguatan politik identitas pada politik elektoral perlu diatensi secara serius oleh segenap komponen bangsa, terlebih lagi partai politik sebagai pilar demokrasi.
Dalam konteks demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia, peran partai politik sangatlah penting sebagai pilar demokrasi yang menyelenggarakan fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, kaderisasi politik, komunikasi politik, hingga kandidasi politik pada Pemilu di berbagai jenjang, eksekutif dan legislatif. Dapat dikatakan bahwa partai politik menjadi saluran kunci dan pemegang tiket emas bagi warga negara yang hendak menjadi wakil rakyat di parlemen dan pimpinan nasional di berbagai level pemerintahan. Partai politik menjadi suprastruktur politik yang melakukan penggemblengan dan penyaringan terhadap siapa pun warga negara yang hendak berkontestasi pada politik elektoral.
Berbicara mengenai partai politik pada era saat ini, tidak terlepas dari dinamika partai politik pada era sebelumnya, yakni era orde baru. Pada era orde baru, partai politik tidak berfungsi dengan baik sebagai pilar demokrasi. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah pada masa itu yang melakukan fusi partai politik ke dalam tiga kelompok untuk memudahkan pengawasan terhadap oposisi dan melanggengkan kekuasaan rezim yang berkuasa. Kelompok nasionalis difusikan ke dalam PDI. Kelompok religius difusikan ke dalam PPP. Sedangkan loyalis pemerintah, baik warga negara, birokrasi, maupun angkatan bersenjata difusikan ke dalam Golkar. Dengan fusi ketat sedemikian, otomatis terjadi pengekangan terhadap demokrasi.
Pasca reformasi 1998 meletus, iklim politik mengalami perbaikan. Hal ini menjadi udara segar bagi partai politik untuk merevitalisasi dan mereformasi diri. Pemilu 2004 sebagai Pemilu langsung pertama pada era pasca reformasi diikuti sedikitnya oleh 24 partai politik dari berbagai platform, nasionalis dan religius. Pemilu 2009 diikuti lebih banyak partai politik, yakni 38 partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa iklim demokrasi mulai kondusif bagi warga negara. Aspirasi rakyat yang tersumbat selama 32 tahun kekuasaan Soeharto seakan membutuhkan banyak saluran untuk dimanifestasikan secara konkret dalam politik elektoral. Tak hanya itu, ekosistem demokrasi juga mengalami penguatan dengan munculnya banyak kelompok masyarakat madani sebagai counterpart partai politik, serta pers yang bebas dan independen.
Tantangan demokrasi
Salah satu tantangan berat bagi konsolidasi demokrasi adalah adanya potensi pembalikan terhadap demokrasi. Rezim orde baru yang koruptif dan oligarkis masih menyisakan residu yang pekat pada sistem politik elektoral nasional. Banyak antek-antek orde baru yang bersalin rupa dan mengubah kulitnya menjadi sosok yang mendadak demokratis dan pro-reformasi, hanya sekadar untuk meraih simpati rakyat pada Pemilu. Alhasil, residu ini menjadi patologi sosial politik yang merusak partai politik. Patologi ini dapat dilihat dari menguatnya oligarki elit di partai politik, kentalnya politik transaksional dalam Pemilu, lunturnya basis ideologis partai dalam menyuarakan suara rakyat, dan yang paling menyedihkan adalah digunakannya politik identitas sebagai strategi untuk memenangkan Pemilu.
Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2014 dan 2019 dapat disebut sebagai wajah kelam demokrasi. Partai politik seolah kehilangan kapasitasnya sebagai mesin program-program kerakyatan dan kebangsaan, sekaligus mesin produksi pemimpin di level nasional. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, partai politik lebih suka menempuh jalur pintas, yakni memecah belah masyarakat ke dalam dua kelompok besar, sehingga masyarakat terpolarisasi. Benar ada blunder politik yang dilakukan oleh salah satu kandidat. Akan tetapi blunder politik kandidat tersebut diamplifikasi dan dikomodifikasi secara masif oleh lawan politiknya, sehingga menimbulkan kegaduhan di level akar rumput. Pilkada DKI Jakarta yang seharusnya berdimensi lokal, teramplifikasi dan tereskalasi menjadi isu nasional dalam skala negatif.
Gelaran Pilpres 2014 dan 2019 juga sangat kental dengan nuansa politik identitas. Ada dua kegagalan besar partai politik pada dua kasus Pilpres tersebut. Pertama, oligarki partai politik dalam bentuk ambang batas Pilpres telah berdampak pada sempitnya alternatif pilihan bagi masyarakat, yakni hanya dua pasangan calon. Kedua, penggunaan politik aliran yang notabene merupakan derivasi politik identitas sangat terasa digunakan untuk mendiskriminasi kontestan satu dengan yang lainnya. Situasi tersebut berdampak buruk terhadap demokrasi. Kelembagaan demokrasi melemah, rakyat terpolarisasi, iklim investasi juga memburuk karena adanya distrust dari dunia luar terhadap instabilitas politik di Indonesia.
Penguatan parpol
Pada November 2024 nanti, Indonesia akan menggelar Pilkada serentak untuk level provinsi, serta kabupaten/kota. Partai politik sebagai pilar utama demokrasi dituntut untuk melaksanakan fungsinya dengan memberikan sebesar-besar kemaslahatan bagi rakyat. Oleh karenanya, penguatan partai politik adalah kunci untuk mereduksi penggunaan politik identitas pada Pemilu guna mewujudkan konsolidasi demokrasi. Partai politik seyogianya kembali ke khittahnya sebagai pilar demokrasi yang menjalankan secara konsekuen fungsi-fungsi politik yang diemban, terutama kaderisasi dan kandidasi politik.
Partai politik perlu mendengarkan aspirasi rakyat, sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi politik sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Ada beberapa langkah konkret dalam rangka penguatan peran partai politik. Pertama, reformasi kultural dan struktural di tubuh partai politik. Perlu campur tangan negara secara terbatas agar dinamika partai politik selaras dengan nilai demokrasi. Kedua, penguatan kaderisasi dan kandidasi politik. Dalam kandidasi politik terkait Pemilu, partai politik kerapkali terjebak pada paradigma pragmatis, yakni memilih kandidat yang diusung berdasarkan pada popularitas dan finansial saja, bukan berdasarkan kapasitas dan integritas. Meskipun partai politik memiliki kader yang mumpuni secara kapasitas, tetapi jika tidak memiliki dukungan finansial, maka kader internal ini sulit diusung. Akibatnya, opsi-opsi yang disajikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan aspirasi. Mereka yang hendak diusung oleh partai politik juga tidak sungkan untuk menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya. Ketiga, perlu revisi terhadap UU Pemilu. Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah mengebiri demokrasi. Konsekuensinya, hanya ada dua pasang calon sebagai opsi terbatas kepada rakyat pada Pilpres 2014 dan 2019. Adanya 3 paslon pada Pilpres 2024 juga terbilang tidak memadai. Dengan opsi yang sedikit tersebut, partai politik kerapkali terjerumus pada penggunaan skema politik identitas untuk menggalang dukungan dan meraih suara rakyat pada kelompok tertentu.
Boy Anugerah, SIP., MSI., MPP.,
Tenaga Ahli di MPR RI

 ---
---