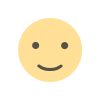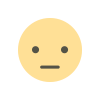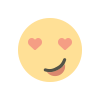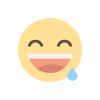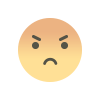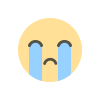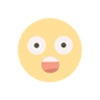PSLH UGM Memfasilitasi Pemkab Maluku Tenggara Rumuskan Kebijakan Lingkungan
KLHS merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak bisa terpisahkan dari RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 - 2045.
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Sebagai penegasan komitmen mewujudkan cita-cita Sustainable Development Goals (SDG’s) ke-17 yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara merumuskan kebijakan dan program penataan lingkungan.
Dua orang tim dari PSLH UGM masing-masing Ahsan Nurhadi M Eng dan Rahula Hangga Nurhendro S Si selama beberapa bulan menjadi fasilitator penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai satu kesatuan perencanaan yang tidak bisa terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 - 2045.
Kehadiran mereka sekaligus sebagai representasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
Ahsan Nurhadi di kantornya pekan lalu menjelaskan dokumen KLHS meliputi antara lain permasalahan dalam Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Sasaran Pokok Daerah, selanjutnya mengerucut dalam empat tahapan arah kebijakan.
Yaitu, Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) dengan fokus Perkuatan Fondasi Transformasi dan Arah Kebijakan Tahap II dengan rentang waktu 2030-2034 difokuskan pada Akselerasi Transformasi. Kemudian, Arah Kebijakan Tahap III rentang waktu 2035-2039 dengan penekanan pada Ekspansi Global serta Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) sebagai Perwujudan Indonesia Emas.
Limbah rumah tangga
Menurut Ahsan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga saat ini perlu memperoleh perhatian serius. Indikatornya dapat dilihat dari jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
"Pengelolaan limbah rumah tangga masih bersifat pribadi dan belum ada pengelolaan limbah rumah tangga secara terpusat," ungkapnya seraya menyarankan pemkab setempat membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat.
Untuk mengurai problem itu, pada kurun waktu 2025-2029 dan 2030-2034 seyogianya dilakukan pengembangan Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD) untuk Gray Water dan Black Water (Komunal dan Individual).
Baru kemudian berlanjut pada tahapan ketiga dan keempat (2035-2039 dan 2040-2045) berupa pengembangan IPAL Komunal berbasis masyarakat pada Kawasan Permukiman yang berdekatan dengan pantai dan kawasan tangkapan air.
Indikator lainnya dapat dilihat dari jumlah produk ramah lingkungan yang belum teregister di dalam pengadaan pemerintah, proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan (indeks tutupan lahan) dan proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Mengendalikan deforestasi
Adapun upaya mendorong penggunaan barang/jasa ramah lingkungan pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah antara lain melalui pembuatan regulasi.
Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan proporsi hutan masih belum baik antara lain deforestasi yang berlebihan, eksploitasi ilegal, konversi lahan untuk pertanian atau perkebunan, kebakaran hutan, dan kurangnya kebijakan konservasi yang efektif.
Menurut Ahsan, permasalahan itu dapat diatasi dengan mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah efektif untuk mengendalikan deforestasi, termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap praktik penebangan liar.
Kebijakan berikutnya diarahkan pada upaya pemulihan dan perlindungan terhadap hutan yang terdegradasi atau terancam, dengan mengimplementasikan program reboisasi dan restorasi hutan.
Sistem pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan perlu ditingkatkan seiring dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan.
Konversi lahan
Konsekuensinya, menurut Ahsan, kebijakan itu perlu disertai dengan memperkuat penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi illegal dan konversi lahan yang merugikan ekosistem hutan.
Langkah terakhir adalah mengembangkan dan menerapkan kebijakan konservasi yang efektif, melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
Rahula Hangga Nurhendro menambahkan, kurangnya alokasi dana dan sumber daya yang memadai menjadi kendala utama menangani proporsi luas lahan kritis.
Selain itu, ketidakpastian terkait kepemilikan dan penggunaan lahan kritis sulitnya mendapatkan izin dan kerja sama dari pemilik lahan, juga menghambat proses rehabilitasi.
Faktor lainnya, lanjut dia, kurangnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam program rehabilitasi lahan kritis yang dapat menghambat keberlanjutan dan keberhasilan upaya tersebut.
Belum lagi adanya pengaruh perubahan iklim seperti cuaca ekstrem dan kekeringan yang berpotensi memperburuk kondisi lahan kritis dan membuat proses rehabilitasi menjadi lebih sulit.
Kabupaten Maluku Tenggara yang terbagi atas 190 Ohoi/Desa dan 1 Kelurahan terletak pada posisi yang cukup strategis. Wilayah itu diapit dua lautan besar, Laut Banda dan Laut Arafura. (*)

 Redaktur
Redaktur