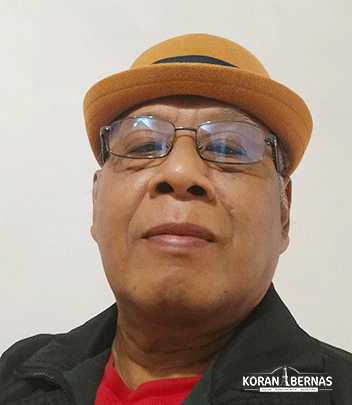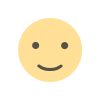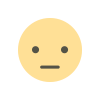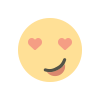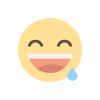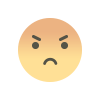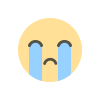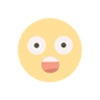Egalitarian dalam Hukum
Oleh: Sudjito Atmoredjo
Indonesia saat ini, tampaknya mengalami nasib buruk serupa, atau lebih buruk dari itu. Untuk mengubah nasib buruk tersebut, dan menjadikannya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hemat saya, kembali ke Pancasila dan pemberlakuan UUD 1945 asli, merupakan langkah elegan. Dalam tekad dan semangat demikian, doktrin egalitarian wajib, layak, dan patut didekonstruksi dan ditransformasikan ke doktrin keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam doktrin ini, proporsionalitas hak dan kewajiban, proporsionalitas tugas dan tanggung-jawab, keberlakuan hukum profetik, serta dorongan moral untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, diunggulkan daripada sekadar berhukum secara rutinitas.
DOKTRIN egalitarian dalam hukum, begitu menonjol dalam kehidupan modern. Doktrin ini memuncak penggunaannya sejak abad ke-19, khususnya di Eropa, untuk kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan doktrin ini, tergusurlah doktrin-doktrin yang berlaku pada ancient regime, semisal dominasi golongan gereja, golongan ningrat, golongan prajurit, golongan darah biru dan sebagainya.
Sejak saat itu, dengan dalih demi keadilan sosial, hukum berlaku setara bagi semua orang. Sekalian orang, setara di hadapan hukum. Kesetaraan adalah kata kuncinya. Tidak ada lagi individu, kelompok, golongan, yang dipandang remeh ataupun lebih unggul di atas yang lainnya.
Keberlanjutan dari doktrin egalitarian antara lain munculnya negara konstitusi. Dengan slogan “supremasi hukum”, maka konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara. Di dalam konstitusi itulah, segala hasrat, wawasan ke depan, garis-garis haluan, visi-misi, dan pola kehidupan bernegara diatur pokok-pokoknya. Seterusnya, berbagai hukum (perundang-undangan) dibuat dan diberlakukan sesuai/konsisten dengan konstitusi. Tiadalah sesuatu dipandang benar, kecuali dapat dipertanggungjawabkan kepada konstitusi.
Seiring dengan dominasi konstitusi, maka keberadaan dan fungsi konvensi, hukum adat, kebiasaan, doktrin/hukum agama, dipinggirkan. Seluruh tatanan itu dipandang telah out of date. Hanya boleh dan bisa diberlakukan bila oleh penguasa dipandang mendukung pemberlakuan konstitusi.
Untuk diingat, bahwa doktrin egalitarian bukanlah idealitas untuk kehidupan bernegara secara universal. Kehidupan tradisional, kehidupan religius, kehidupan kekeluargaan, kehidupan berkasta, tiadalah mungkin dihapuskan oleh orang-orang modern bermodalkan doktrin egalitarian. Betapapun, dinamika kehidupan mengalami pasang-surut, namun kehidupan alami, natural, dan kodrati, akan terus mencari celah-celah untuk tetap bertahan. Dengan kata lain, tiadalah mungkin seluruh kehidupan ditransformasikan ke alam modernitas, dan tiada mungkin pula kebhinekaan dan pelapisan sosial digantikan dengan kesetaraan melalui rekayasa artifisial.
Sebagaimana terlihat dan terasakan dalam kehidupan bernegara saat ini, semangat dan idealitas pemberlakuan doktrin egalitarian, senantiasa sarat dengan upaya-upaya dan rekayasa teknis, prosedural, dan birokratis. Para pemegang kekuasaan tiadalah rela disetarakan dengan rakyat. Melalui rekayasa konstitusi, undang-undang, dan pasal serta ayat yang ada di dalamnya, apa yang disebut sebagai supremasi hukum, dirumuskan dalam teks-teks multi-tafsir. Dari celah itulah, maka kebenaran hukum sangat tergantung pada penafsiran penguasa. Betapapun kedaulatan (kekuasaan tertinggi) ada pada rakyat, namun tiadalah mungkin rakyat diunggulkan untuk penafsiran hukum itu.
Kelemahan-kelemahan doktrin egalitarian, telah memicu munculnya kritik-kritik tajam terhadapnya. Ambil contoh. Idealitas tentang non-diskriminasi, sebagai penjabaran dari makna kesetaraan. Idealitas itu, tiada pernah mampu menghalau kategori the haves versus the haves-nots. Realitas empiris selalu memperlihatkan, bahwa ketika ada kasus, perselisihan, sengketa, maka melalui tafsir konstitusi, undang-undang, pasal dan ayat, pastilah golongan the haves yang menjadi penentu, pemenang, dan penerima manfaat berlakunya hukum. Artinya egalitarian itu omong kosong.
Garry Spencer, dalam With Justice for None (1789) mengingatkan bahwa di Amerika, dalam banyak kasus yang melibatkan penguasa (politikus, birokrat, oligarki, pengusaha, dan keluarganya), penyelesaiannya selalu mendayakan keunggulan fulus/duit, keberlimpahan kekuasaan, kekuatan (legal maupun ala preman), dan kelengkapan fasilitas. Segalanya, didayagunakan secara represif dan masif, untuk pemenangan perkaranya. Bahkan tidak segan-segan, siapapun terindikasi mengganggu kemapanan, kenyamanan, dan kepentingannya, akan dikriminalisasikan.
Mestinya pernyataan Spencer tersebut, diperhatikan dan dijadikan pembelajaran untuk pembangunan hukum secara keseluruhan. Sayang, peringatan ilmuwan kesohor itu dipandang sebelah-mata oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia. Sebaliknya, justru pola perilaku nista diikuti, dikembangkan, dipolakan, dan dilembagakan. Mereka bermain-main dalam pusaran doktrin egalitarian. Pemikiran, sikap, dan pemikiran demikian diawali dengan mengamandemen UUD 1945 hingga empat kali, hingga berlanjut pada perilaku sok kuasa.
Perihal amandemen terhadap UUD 1945, barangkali kita bisa berbeda pendapat. Walau demikian, satu hal yang pasti, bahwa sejak ditinggalkannya UUD 1945 asli dan serta-merta diberlakukannya UUD hasil amandemen, kehidupan bernegara sarat dengan perilaku individual, liberal, materialistis, kapitalistik, dan sekuler. Karakter bangsa, seperti: gotong-royong, musyawarah, empati, simpati, tenggang rasa, dugo-prayoga, kekeluargaan sebagai bangsa, menjunjung tinggi akhlak/moral/etika, telah banyak ditinggalkan, sehingga hanya menjadi kenangan masa lalu.
Kini, atas nama egalitarian, demokrasi, atau kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi terpecah-belah. Kebersatuan dikoyak-koyak melalui rekayasa hukum, politik, dan kekuasaan. Ambil contoh. Keterbelahan aparat penegak hukum. TNI diperbantukan ke Kejaksaan. Tentu, agar aman, nyaman, dan terlindungi dalam melakukan tugas-tugasnya. Pada kasus demikian, banyak orang bertanya, siapa yang mengancam Kejaksaan, mengapa ada ancaman, ke mana arah dan apa tujuan ancaman, dan sebagainya. Karena berbagai pertanyaan tersebut, tak cukup dijawab secara normatif, maka dilakukanlah kebijakan/langkah konkrit. Kebijakan ini sama sekali tak ada keterkaitannya dengan doktrin egalitarian.
Sejujurnya, di tengah memudarnya supremasi akhlak/moral/etika dalam bernegara, dan sejurus dengan itu rona kehidupan harmonis, kekeluargaan, aman, damai, semakin kering-kerontang dan keras, banyak pihak (orang sehat) berkeinginan agar pola kehidupan dibenahi total. Keinginan demikian, hemat saya, logis dan wajar.
Pengamat dan pengiritk demokrasi-liberal, Francis Fukuyama dalam The End of History and Last Man (1992) menyatakan banyak orang Amerika menagis ketika negara itu mengalami derogasi, dan demokrasi dipraktikkan oleh men without chests. Secara praksis dan empiris, demokrasi liberal ditegakkan tanpa elan perjuangan revolusionernya sebagai human, melainkan sekadar rutinitas memuakkan.
Indonesia saat ini, tampaknya mengalami nasib buruk serupa, atau lebih buruk dari itu. Untuk mengubah nasib buruk tersebut, dan menjadikannya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hemat saya, kembali ke Pancasila dan pemberlakuan UUD 1945 asli, merupakan langkah elegan. Dalam tekad dan semangat demikian, doktrin egalitarian wajib, layak, dan patut didekonstruksi dan ditransformasikan ke doktrin keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam doktrin ini, proporsionalitas hak dan kewajiban, proporsionalitas tugas dan tanggung-jawab, keberlakuan hukum profetik, serta dorongan moral untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, diunggulkan daripada sekadar berhukum secara rutinitas.
Dalam pada itu, dorongan nafsu duniawi untuk terus berebut kekuasaan, berlomba-lomba menumpuk harta, serta perilaku kelewat batas, perlu dikendalikan. Tak kalah pentingnya, wawasan kebangsaan (nasionalisme) wajib diunggulkan daripada wawasan global (internasionalisme). Wallahu’alam. ***
Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, S.H., M.Si.
Guru Besar pada Sekolah Pascasarjana UGM

 ---
---