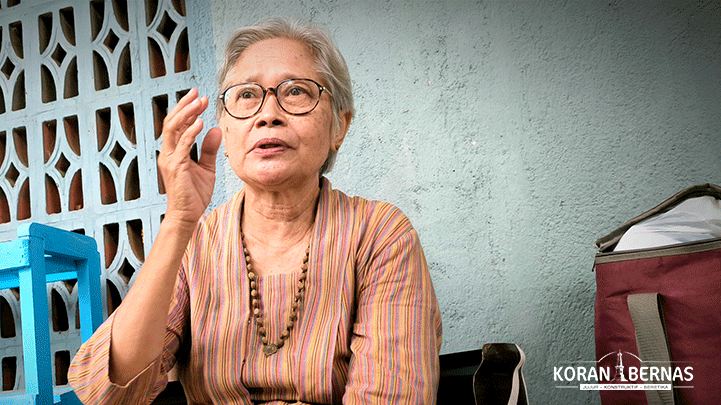Belajar dari Peristiwa, Sekolah Hafalan vs Sekolah Kehidupan
Oleh: Sri Wahyaningsih
Kurikulum Merdeka yang rohnya ada pada pendidikan berpusat pada anak, baru sebatas jargon. Karena anak tetap diharuskan menempuh pelajaran yang sama. Anak belum merdeka memilih tema-tema belajar yang menjadi minatnya. Perubahannya paling banter pada metode mengajar yang kreatif, seru dengan alat pendukung yang canggih. Tetapi bukan pada kemerdekaan memilih konten yang sesuai dengan minatnya. Sekolah-sekolah masih menerapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Mau tidak mau semua anak harus menempuh pelajaran yang sama, terlepas berminat atau tidak.
BANYAK orang beranggapan, belajar itu identik dengan duduk manis, membaca buku pelajaran, menghafal rumus-rumus. Maka di beberapa daerah dicanangkan program belajar masyarakat pada jam 18-21. Artinya pada jam tersebut anak-anak harap di rumah membaca buku pelajaran, mengerjakan PR, menghafal teks yang akan diajarkan bapak atau ibu guru besuk di sekolah. Belajar identik dengan menghafal.
Membaca buku tentunya penting karena dapat membuka wawasan. Tetapi jangan sebatas buku pelajaran atau modul saja. Buku-buku pengetahuan umum, buku tentang seluk beluk kehidupan, novel atau buku sastra juga penting. Selain dapat mengasah pikiran juga dapat mengasah batin manusia.
Belajar dengan cara menghafal akan membebani otak karena harus mengingat-ingat. Pada waktu tertentu hafalan akan hilang tak berkesan. Anak seperti dipaksa harus belajar sesuatu yang belum tentu mereka butuhkan. Guru banyak memegang kendali, menentukan materi apa yang harus dipelajari. Anak lebih banyak pasif, seandainya aktif pun sebatas materi yang sudah ditentukan. Interaksinya bisa dengan diskusi namun bukan diskusi dengan topik yang betul-betul riil. Kadang hanya simulasi, bukan persoalan yang sesungguhnya terjadi atau dihadapi.
Berbeda dengan belajar melalui peristiwa yang nyata atau riil. Anak-anak akan menghadapi secara langsung, mulai dari melihat, mengamati, meneliti, menganalisa sampai kepada mengambil kesimpulan. Secara emosi anak ikut terlibat dalam menggali pengetahuan dari obyek yang mereka amati. Mereka belajar mencari pemecahan masalah ketika menemui persoalan sehingga pikirannya terasah. Belajar melalui peristiwa yang nyata ini, kami sebut sebagai sekolah kehidupan. Prakteknya kami jalankan dengan metode riset. Ki Hadjar Dewantara menyebutnya dengan Nitèni, Nirokké dan Nambahi, atau mengamati, menirukan-mencoba-coba-mengeksplorasi kemudian menambahi atau menginovasi.
Perubahan kurikulum yang sering terjadi seiring dengan pergantian menteri pendidikan di negeri ini, acap kali tidak menyentuh hal-hal yang esensial dalam belajar. Setidaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, sudah ada empat kali pergantian kurikulum. Pada tahun 2004 ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, tahun 2006 berganti dengan KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan lalu tahun 2013 berganti menjadi K-13 dan pada tahun 2021 menggunakan kurikulum merdeka terbatas pada sekolah penggerak. Pada 2022/2023 secara bertahap dipraktekkan di semua sekolah dari PAUD hingga sekolah menengah. Pada tahun 2024 kurikulum merdeka ditetapkan sebagai kurikulum nasional berdasarkan Permendikbudristek No 12 tahun 2024.
Namun perubahan kurikulum tersebut belum menyentuh pada persoalan yang esensial. Kurikulum masih banyak berkutat pada metode saja, belum sampai kepada perubahan paradigma. Akibatnya, proses belajar yang terjadi di sekolah tidak terlalu signifikan dengan perubahan kurikulum. Guru tetap saja menjadi pengajar dan sumber belajar satu-satunya. Sementara murid menjadi pendengar. Sekalipun Pada kurikulum merdeka ada pendekatan belajar berbasis proyek, namun tema sering kali sudah ditentukan oleh guru. Proses belajar yang dialogis belum mendapatkan ruang yang memadai.
Kurikulum Merdeka yang rohnya ada pada pendidikan berpusat pada anak, baru sebatas jargon. Karena anak tetap diharuskan menempuh pelajaran yang sama. Anak belum merdeka memilih tema-tema belajar yang menjadi minatnya. Perubahannya paling banter pada metode mengajar yang kreatif, seru dengan alat pendukung yang canggih. Tetapi bukan pada kemerdekaan memilih konten yang sesuai dengan minatnya. Sekolah-sekolah masih menerapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Mau tidak mau semua anak harus menempuh pelajaran yang sama, terlepas berminat atau tidak.
Pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, dunia seakan terbuka. Setiap orang dapat secara mandiri belajar melalui internet. Apabila guru tetap mengajar, atau sekadar memindahkan pengetahuan saja, maka dapat dipastikan akan ketinggalan. Goggle dan Artificial Intelegence (AI) tentu lebih cepat. Tantangan bagi guru untuk dapat mengubah dirinya menjadi fasilitator merupakan kebutuhan mutlak. Bagaimanapun juga guru seyogyanya dapat menyesuaikan diri dengan zaman. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Apabila tidak demikian maka anak merasa tidak terfasilitasi kebutuhannya, sehingga muncul hal-hal yang tidak kita inginkan seperti, mogok sekolah, tawuran dan lain sebagainya. Anak juga tidak dapat menemukan potensi baiknya sebagai bekal hidup. Bahkan mungkin mereka hanya akan menjadi follower belaka, tidak kreatif, takut mengambil keputusan dan tidak mandiri.
Merdeka belajar sudah memberi ruang yang leluasa baik kepada guru maupun anak, namun belum semua guru mempunyai ketetapan hati memberi kepercayaan kepada anak, untuk belajar sesuai dengan ketertarikan masing-masing. Guru masih “ketonto” untuk mengajar. Sibuk dengan urusan administrasi. Takut anak tidak mampu. Atau jangan-jangan guru belum menguasai metodologinya, sehingga banyak guru berkomentar dengan kurikulum merdeka ini justru membingungkan dan menambah beban administrasi. Merdeka yang tidak merdeka.
Kuncinya sebetulnya ada pada perubahan paradigma. Bagaimana memandang anak. Bagaimana peran fasilitator. Apa saja sumber-sumber belajar yang dapat digunakan. Pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam proses belajar. Sarana prasarana seperti apa yang dapat mendukung proses belajar dan seterusnya. Ketika kita memandang anak sebagai pribadi yang berdaya dan masing-masing memikili keunikan, kecenderungan yang berbeda beda, pastilah kita tidak memperlakukan mereka secara seragam. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, dan anak menjadi guru atas dirinya sendiri. Dengan demikian anak bertanggung jawab atas perkembangan dirinya. Berani mengambil keputusan untuk belajar sesuai dengan minatnya.
Sebagai fasilitator, guru memfasilitasi kebutuhan anak. Menuntun, bukan menggurui, sehingga anak akan menemukan dan mengembangkan potensinya dengan merdeka. Guru perlu memahami kondisi anak didik secara mendalam. Tidak hanya kenal nama, tetapi juga tahu kondisi fisik dan mentalnya. Mengetahui minat atau kecenderungannya, kendala yang dihadapi, daya dukung keluarganya atau lingkungan terdekatnya. Assesment awal sangat diperlukan dalam proses belajar yang basisnya bukan hafalan. Anak butuh penguatan untuk meneguhkan pilihannya, Guru serta orang tua membutuhkan informasi apa yang diperlukan anak sehingga dapat memfasilitasi kebutuhannya.
Proses belajar melalui pendekatan riset, dialog menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Guru tidak dapat hanya memberi instruksi saja. Guru harus dapat memantik melalui pertanyaan-pertanyaan analitis, sehingga anak dapat mengembangkan pengetahuan. Guru harus memiliki orientasi dari apa yang dilakukan anak, sehingga baik guru maupun anak harus belajar. Basis dari riset adalah rasa ingin tahu. Bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Boleh dikatakan sebagai sekolah bertanya. Selama ini anak dibiasakan menjawab pertanyaan guru yang jawabannya sudah disediakan, sehingga kadang anak tidak memahami dengan mendalam persoalannya bahkan sering menjawab asal saja.
Sebentar lagi akan ada perubahan kabinet, bisa jadi menteri pendidikan akan ganti. Apakah kurikulum juga akan ganti? Menjadi tanda tanya besar. Apapun kurikulumnya, jika kita menangkap esensinya, sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Pengalaman SALAM (Sanggar Anak Alam) selama 24 tahun mengelola sekolah dengan kurikulum kehidupan, masing-masing anak boleh memilih materi belajar sesuai ketertarikan masing-masing, tidak pernah terpengaruh dengan perubahan tersebut.
Bagaimana menjadikan belajar sebagai proses yang bermakna dan menjawab kebutuhan setiap anak? Kita harus mempunyai paradigma atau perspektif bahwa setiap anak adalah pribadi yang berdaya, unik, masing-masing mempunyai potensi atau kodrat alam yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki cara belajar dan memecahkan masalah yang berbeda pula.
Dengan cara pandang tersebut, maka proses belajar di sekolah yang cenderung menyeragamkan dengan pendekatan mata pelajaran menjadi tidak cocok. Penyeragaman berarti tidak menghormati atau menghargai keragaman anak. Tidak menghormati potensi anak, bahkan dapat dikatakan membelenggu potensi anak.
Merdeka belajar dapat dijadikan pintu masuk untuk memfasilitasi anak menemukan jati diri dan menghargai orang lain sebagai sesama. Dengan demikian semua orang dapat maju bersama membangun kehidupan yang lebih baik dan tertib damai. Tidak ada persaingan untuk menang sendiri. Setiap anak akan menjadi juara atas dirinya sendiri. Belajar bukan lagi menjadi beban namun belajar merupakan kebutuhan setiap orang untuk tumbuh dan berkembang. Mana yang lebih cocok sekolah hafalan atau sekolah kehidupan? Semua tergantung pilihan masing-masing, karena setiap pilihan ada konsekwensinya. Selamat berproses. *
Sri Wahyaningsih
Dewan Pembina Sanggar Anak Alam Yogyakarta.

 ---
---