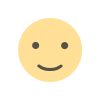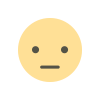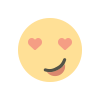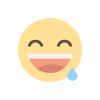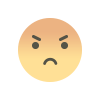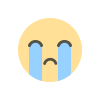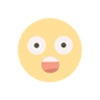Partai Politik Pasca Pemilu 2024
Oleh: Boy Anugerah
Situasi dan kondisi sedemikian menimbulkan konsekuensi politik baik bagi parpol sendiri maupun rakyat. Ketidaksinkronan sikap politik dan arah gerak parpol pada Pilpres dan Pilkada secara gradual akan menimbulkan citra di masyarakat, khususnya elemen terdidik, bahwa parpol lebih cenderung bersikap pragmatis ketimbang ideologis. Pada kasus Pilkada Sumut misalnya, sikap politik Nasdem yang menentang politik dinasti Jokowi pada Pilpres justru bertolak belakang dengan dukungan Nasdem pada Bobby Nasution sebagai cagub yang notabene adalah menantu Jokowi. Demikian pula halnya dalam kasus Pilkada Jakarta, dalam hal mana terbuka peluang koalisi antara PDI-P dan PKS dalam mengusung Anies Baswedan. Perbedaan tajam sikap politik pada Pilpres, serta ideologi yang dianut oleh masing-masing parpol tersebut seakan cair karena tingginya elektabilitas Anies Baswedan di Jakarta. Matematika politik akan kekuasaan menjadi kompas terdepan dalam menjalani dinamika Pilkada.
RANGKAIAN Pemilu 2024 memang belum rampung. Setelah menyelesaikan Pilpres dan Pileg pada Februari lalu, tak lama lagi kita akan menyongsong gelaran pesta demokrasi yang tak kalah seru, dinamis, dan menentukan masa depan bangsa Indonesia, yakni Pilkada serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ada yang menarik dari rangkaian Pemilu tersebut, yakni arah gerak, manuver, dan orientasi yang hendak dicapai oleh partai politik (parpol) sebagai kontestan Pemilu. Menarik untuk menimbang apakah diskrepansi sikap politik parpol pada masing-masing level kontestasi akan menentukan eksistensi dan kualitas parpol tersebut ke depan sebagai pilar demokrasi?
Pilar demokrasi
Parpol adalah pilar demokrasi. Pelabelan ini tidak terlepas dari tugas dasar yang diemban oleh parpol sebagai entitas sosial budaya dan politik yang menjalankan proses rekrutmen, kaderisasi, komunikasi, partisipasi, hingga kandidasi politik. Dalam konteks Pemilu, dengan beragam levelnya, parpol merupakan elemen kunci dan fundamental. Dalam kerangka sistem politik Indonesia, suatu gelaran Pilpres hanya boleh diikuti oleh calon yang diajukan oleh parpol dan/atau koalisi parpol yang memenuhi ambang batas 20 persen kursi parlemen. Hal ini juga berlaku pada perhelatan Pilkada. Pada kontestasi Pileg, parpol memegang kuasa penuh untuk kandidasi politik.
Sebagai pilar demokrasi, parpol mengemban amanat rakyat dan diharapkan tunduk pada konsepsi daulat rakyat yang kita junjung sebagai negara republik. Sebagai pilar demokrasi, parpol juga berperan sebagai mesin artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat yang diwakili sesuai dengan ideologi dan arah perjuangan yang dianut. Ini kredo-kredo politik mendasar yang seharusnya dipegang oleh parpol. Namun demikian, kita tidak bisa menafikan bahwa parpol juga merupakan instrumen kekuasaan (instrument of pursuing power). Terkait hal itu, seringkali terjadi diskrepansi antara apa yang diharapkan (das sollen) oleh rakyat dan praksis yang dijalankan (das sein).
Pemilu 2024 menjadi laboratorium sosiopolitik yang pas untuk menguji tesis tersebut. Dalam konteks Pilpres, arah gerak dan manuver parpol dalam mengusung capres dan cawapres akan sangat ditentukan oleh elektabilitas paslon yang diusung. Tentu ada variabel-variabel lainnya seperti upaya untuk menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) bagi parpol pendatang, strategi untuk menaikkan perolehan suara dan kursi bagi parpol eksisting, mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari pengusungan kader sendiri dalam kandidasi Pilpres, serta mengonsolidasi seluruh mesin pemenangan (simpatisan dan relawan). Pada Pilpres 2024 kita menyaksikan adanya poros keberlanjutan yang berhadapan dengan poros perubahan.
Diskrepansi dan konsekuensi
Mari bandingkan arah gerak parpol pada Pilpres tersebut dengan arah gerak dan manuver parpol dalam menyongsong Pilkada 2024 saat ini. Dikotomi politik antara poros keberlanjutan dan poros perubahan sebagai produk Pilpres yang lalu mulai samar, untuk tidak menyebut nihil keberadaannya pada Pilkada nanti. Pasca penetapan KPU mengenai paslon yang keluar sebagai pemenang Pilpres, parpol yang berada di luar barisan pengusung the champ (parpol-parpol non-KIM) seperti PPP dan Nasdem, sudah melakukan manuver tajam dan menunjukkan kecenderungan koalisi. Bahkan ada salah satu ketum parpol yang tak segan-segan menunjukkan kecenderungan koalisi dengan Prabowo-Gibran (baca; langsung menemui Jokowi) pasca hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei.
Ketidaksinkronan sikap politik, arah gerak, dan orientasi parpol pada perhelatan Pilpres dan Pilkada tentu bukan barang baru dalam perhelatan Pemilu di Indonesia. Fenomena ini muncul karena beberapa faktor. Pertama, komitmen parpol untuk berkhidmat pada ideologi dan garis perjuangan belum cukup kuat. Ideologi terkadang bisa dikesampingkan jika tebentur dengan matematika politik untuk mendapatkan kekuasaan. Kedua, rezim Pemilu di Indonesia dilimitasi oleh regulasi kuantitatif dalam undang-undang, yakni adanya ambang batas parlemen 20 persen kursi yang harus dipenuhi. Sebagai konsekuensinya, lagi-lagi parpol harus mengesampingkan ideologinya. Ketiga, elitisme parpol di Indonesia masih sangat kuat. Tekadang kebijakan parpol dalam Pemilu tidak selaras dengan aspirasi akar rumputnya, lebih bersifat top-down dari elit parpol.
Situasi dan kondisi sedemikian menimbulkan konsekuensi politik baik bagi parpol sendiri maupun rakyat. Ketidaksinkronan sikap politik dan arah gerak parpol pada Pilpres dan Pilkada secara gradual akan menimbulkan citra di masyarakat, khususnya elemen terdidik, bahwa parpol lebih cenderung bersikap pragmatis ketimbang ideologis. Pada kasus Pilkada Sumut misalnya, sikap politik Nasdem yang menentang politik dinasti Jokowi pada Pilpres justru bertolak belakang dengan dukungan Nasdem pada Bobby Nasution sebagai cagub yang notabene adalah menantu Jokowi. Demikian pula halnya dalam kasus Pilkada Jakarta, dalam hal mana terbuka peluang koalisi antara PDI-P dan PKS dalam mengusung Anies Baswedan. Perbedaan tajam sikap politik pada Pilpres, serta ideologi yang dianut oleh masing-masing parpol tersebut seakan cair karena tingginya elektabilitas Anies Baswedan di Jakarta. Matematika politik akan kekuasaan menjadi kompas terdepan dalam menjalani dinamika Pilkada.
Kompas demokrasi
Yang menjadi pertanyaan menarik untuk diketengahkan adalah bagaimana posisi diskrepansi sikap politik parpol ini jika ditimbang dari kompas demokrasi? Mengapa demokasi yang menjadi tolok ukurnya? Tentu jawabannya adalah dengan mengembalikan kembali posisi parpol sebagai pilar demokrasi. Berbicara demokrasi adalah berbicara mengenai daulat rakyat, bagaimana rakyat bisa dijembatani aspirasi dan keinginannya, tercapai kebutuhan dasarnya sebagai warga negara melalui artikulasi dan agregasi kepentingan yang dijalankan oleh parpol. Pengukuhan kedaulatan rakyat dan pemenuhan aspirasi rakyat akan sulit terpenuhi jika wajah parpol dualistik pada aras pusat dan daerah. Sikap politik parpol yang direpresentasikan oleh kepala daerah dan legislatif berpotensi menghadirkan wajah yang kontradiktif antara aras pusat dan daerah. Hal ini menjadi sinyal buruk bagi pelaksanaan proses pembangunan nasional dan formulasi kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Jika parpol mau mencermati resultante Pilpres 2024 yang lalu, dalam hal mana fenomena split ticket voting begitu mencuat, maka parpol akan menyadari betapa penting untuk berkhidmat pada ideologi dan garis perjuangan dengan membuka mata dan telinga selebar mungkin untuk menyerap aspirasi akar rumput mereka. Split ticket voting yang berarti adanya selisih antara total suara yang didapatkan pada Pilpres (calon yang diusung) dengan total suara para pengusung capres-cawapres di Pileg menjadi potret bahwa kemauan elit parpol tidak selamanya simetris dengan kemauan akar rumput. Elit selalu bergerak di tataran pursuing of power, sementara akar rumput jamaknya bergerak pada aras ideologi parpol. PDI-P yang notabene adalah parpol terbesar di Indonesia begitu terdampak oleh fenomena split ticket voting ini. Status sebagai the champ pada Pileg 2024 tidak simetris dengan perolehan suara Ganjar-Mahfud yang mereka usung. Boleh jadi PDI-P menilai ini sebagai situasi anomali politik. Setiap parpol selalu punya rasionalisasi untuk sirkumstansi yang mereka hadapi.
Kita, sebagai rakyat, tentu menaruh harapan besar pada parpol sebagai kepanjangan tangan untuk memilih wakil-wakil yang dapat menyuarakan aspirasi. Oleh karenanya, parpol juga dituntut untuk menyelaraskan antara hak dan kewajibannya sebagai entitas politik yang menentukan masa depan demokrasi di Indonesia. Kewenangan besar yang dimiliki oleh parpol dalam rekrutmen dan kandidasi politik pada Pemilu harus diikuti tanggung jawab besar untuk memperjuangkan aspirasi yang dititipkan oleh rakyat. Jangan sampai rakyat difait-accompli oleh parpol untuk memilih calon-calon pemimpin yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan mereka. Di sisi lain, dari perspektif bangsa dan negara, konsistensi dan komitmen parpol akan menentukan arah gerak konsolidasi demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia saat ini. Pertanyaan yang layak diketengahkan, apakah demokrasi matang (mature democracy) sebagai tahap optimum demokrasi dapat terwujud ketika parpol masih bergerak dalam pragmatisme politik dan kekuasaan? Silakan dijawab. ***
Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P.
Alumnus Pasca Sarjana Kajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia/Tenaga Ahli di MPR RI

 ---
---