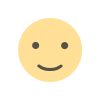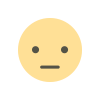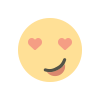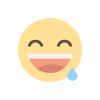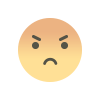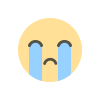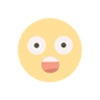Seberapa Penting Haluan Negara bagi Kita?
Oleh: Boy Anugerah
Kerapkali kita melihat bagaimana seorang gubernur berbeda pendapat dengan bupati/walikota. Di Jawa Tengah, ada gubernur yang berbeda pendapat dengan walikota terkait pembangunan pusat perbelanjaan. Pada masa pandemi Covid-19 yang lalu, kita juga menyaksikan bagaimana pejabat di level pusat yang diberikan kewenangan dalam pengendalian pandemi berbeda pandangan dengan kepala daerah dalam hal mitigasi penyebaran Covid-19. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan tanpa haluan yang jelas dan mengikat, akan sangat ditentukan oleh persepsi siapa yang berkuasa, apalagi yang berkuasa terpilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) Periode 2019-2024 akan menyelesaikan masa baktinya dalam beberapa bulan ke depan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah dokumen Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang siap dieksekusi oleh MPR RI periode selanjutnya. PPHN ini dipandang penting untuk ditindaklanjuti sebagai solusi komprehensif atas model pembangunan nasional saat ini, yang tersandera oleh mekanisme politik elektoral dan terkesan tidak ada kesinambungan.
Jangkankan koherensi dan kontinuitas di level pusat, pembangunan di aras pusat dan daerah seringkali berbenturan satu sama lain. Pokok pangkalnya adalah skema pembangunan yang ditentukan oleh visi misi dan program kerja pemenang Pemilu. Pada masa lalu, kita mengenal adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan pembangunan nasional pada era orde baru. Kebijakan pembangunan nasional di level pusat dan daerah pada masa itu harus berpedoman pada GBHN.
Ketika reformasi politik terjadi pada 1998 yang diikuti dengan dilakukannya beberapa kali amandemen konstitusi, keberadaan GBHN dihapus. Hal ini bersamaan dengan perubahan status MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, serta perubahan mekanisme Pilpres dari bersifat representatif (dipilih oleh MPR RI) menjadi Pilpres secara langsung dengan rakyat sebagai voters.
Perubahan-perubahan melalui amandemen konstitusi tersebut di satu sisi memperkuat sistem presidensial. Namun di sisi lain, berimplikasi pada lahirnya model pembangunan nasional yang ditentukan oleh perspektif atau pandangan para pemenang politik elektoral. Model pembangunan nasional pada era pasca reformasi merujuk pada visi misi dan program kerja pemenang Pemilu. Sebagai contoh, ketika seorang capres terpilih dalam Pemilu, maka RPJMN dan Renstra K/L akan diformulasi sesuai dengan visi misi dan program kerja yang ia usung.
Perbandingan
Pada masa SBY yang menjabat sebagai Presiden RI 2004-2009 dan 2009-2014, kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan sesuai visi misi yang diusung, yakni thousand friends and zero enemy. Visi misi ini secara konkret dimanifestasikan dalam bentuk keterlibatan aktif Indonesia di forum-forum internasional. Pada masa Jokowi, skema politik luar negeri thousand friends and zero enemy ini tidak berlanjut. Politik luar negeri Indonesia pada era Jokowi lebih bersifat pasif dan seremonial.
Sebagai perbandingan lainnya, pembangunan nasional pada era SBY lebih banyak menyasar pembangunan ekonomi masyarakat, seperti pembukaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, sedangkan pada era Jokowi, pembangunan berfokus pada infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, tol, dan pelabuhaan untuk memperbesar investasi. Sengaja komparasi yang dilakukan merujuk pada SBY dan Jokowi karena keduanya merupakan produk Pilpres secara langsung hasil amandemen konstitusi.
Meskipun berbeda dalam hal kebijakan luar negeri dan model pembangunan domestik, baik SBY dan Jokowi bisa dikatakan gagal dalam pembangunan HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu seperti G-30S/PKI, Tanjung Priok, Trisakti, Semanggi, dan Munir tidak kunjung bisa diselesaikan. Apa poin penting yang bisa ditarik dari contoh-contoh kasus yang saya sampaikan di sini?
Pertama, model pembangunan nasional tanpa panduan atau pedoman yang jelas akan sangat ditentukan oleh selera pemenang Pemilu. Faktor idiosinkratik (latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan) SBY yang berlatar belakang militer tentu berbeda dengan idiosinkratik Jokowi yang sipil murni. Akibatnya, perspektif mereka selaku penguasa akan sangat ditentukan oleh idiosinkratik yang melekat pada mereka.
Kedua, model pembangunan nasional tanpa haluan yang jelas tidak akan komprehensif dalam menyelesaikan kebutuhan bangsa. Pembangunan nasional di sini tidak hanya ekonomi, tapi juga hal-hal lain yang bersifat kritikal seperti demokrasi, hak asasi manusia, bahkan pembangunan karakter manusia Indonesia sendiri.
Ketidak-ajegan pembangunan antarrezim sejatinya menghadirkan biaya pembangunan yang besar. Biaya pembangunan ini bersumber dari pajak rakyat. Ketidak-ajegan dan nihilnya kontinuitas pada pola pembangunan berdampak pada terbuangnya anggaran secara percuma. Ini hanya mengambil sampel di level pusat, yakni Pilpres, belum jika menghitung di level daerah, yakni sekian provinsi dan kabupaten/kota.
Kerapkali kita melihat bagaimana seorang gubernur berbeda pendapat dengan bupati/walikota. Di Jawa Tengah, ada gubernur yang berbeda pendapat dengan walikota terkait pembangunan pusat perbelanjaan. Pada masa pandemi Covid-19 yang lalu, kita juga menyaksikan bagaimana pejabat di level pusat yang diberikan kewenangan dalam pengendalian pandemi berbeda pandangan dengan kepala daerah dalam hal mitigasi penyebaran Covid-19. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan tanpa haluan yang jelas dan mengikat, akan sangat ditentukan oleh persepsi siapa yang berkuasa, apalagi yang berkuasa terpilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu.
Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan menyetujui PPHN yang direkomendasikan oleh MPR RI. Namun, yang menjadi kebutuhan adalah mekanisme pembangunan yang bersifat ajeg dan mampu mencapai tujuan nasional sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Pembangunan yang efektif dan efisien, tidak boros.
Perlu penyempurnaan
Dan, opsi yang cukup rasional dalam mewujudkan kontinuitas pembangunan tersebut ada di skema PPHN yang diusung oleh MPR RI tersebut. Apa yang dihasilkan oleh MPR RI dalam bentuk dokumen PPHN ini bisa dikaji kembali oleh berbagai lapisan masyarakat dan dimintakan saran dan kritik untuk kesempurnaannya. Pada hemat saya, masih ada poin-poin yang perlu disepakati bersama lagi.
Pertama, status hukum PPHN apakah perlu diformulasi ke dalam konstitusi melalui skema amandemen, dituangkan dalam bentuk undang-undang, atau konvensi ketatanegaraan. Masing-masing skema memiliki plus minusnya sendiri. Kedua, ada juga usulan-usulan bahwa PPHN harus memuat target-target pembangunan yang bersifat kuantitatif, sehingga mudah diukur, seperti dalam hal pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, target pembukaan lapangan pekerjaan, serta indikator-indikator pembangunan lainnya. Jangan sampai PPHN hanya berisi hal-hal yang sifatnya normatif.
Salah satu hal yang memantik perdebatan dalam diskursus PPHN adalah ketakutan dari kalangan masyarakat sipil bahwa PPHN ini akan digolkan melalui skema amandemen konstitusi. Mereka khawatir jika ada agenda-agenda lain yang mengikuti yang disusupkan oleh elit-elit politik tertentu melalui amandemen konstitusi tersebut. Kekhawatiran ini merupakan suatu hal yang lumrah di alam demokrasi.
Namun satu hal yang harus digarisbawahi, jika pun amandemen konstitusi dilakukan untuk menggolkan PPHN, maka itu tidak dilakukan melalui skema black box atau tanpa pengawasan rakyat. Restu rakyat tetap menjadi landasan utama. Oleh sebab itu, sekali lagi, PPHN yang sudah dituangkan dalam dokumen dan naskah akademik tersebut perlu dikaji lagi untuk penyempurnaannya. Aspirasi masyarakat harus digali sebanyak-banyaknya. Pancasila dan konstitusi dijadikan sebagai panduan. (*)
Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P.
Alumnus Pasca Sarjana Kajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia/Tenaga Ahli di MPR RI

 ---
---