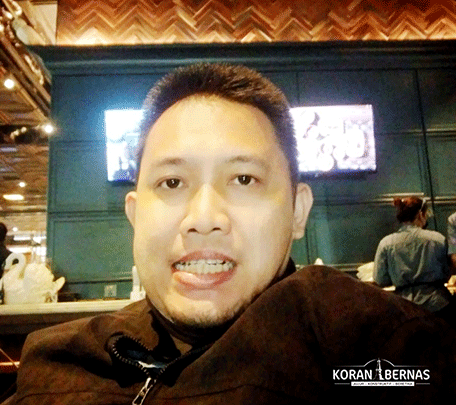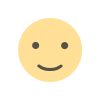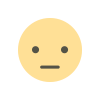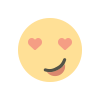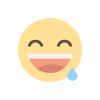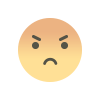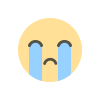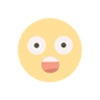Perang Tarif dan Reposisi Sistem Internasional
Oleh: Boy Anugerah
Trump yang memiliki latar belakang yang kuat di bidang ekonomi, sebagai kepala negara menyadari bahwa mereposisi struktur sistem internasional melalui kekuatan militer, tidak akan berjalan efektif dan berpeluang mengulangi kesalahan yang sama di Afghanistan dan Irak. Penggunaan kekuatan militer juga tidak sesuai dengan jiwa zaman yang sudah meninggalkan konflik terbuka apalagi perang. Oleh sebab itu, corak politik dan kebijakan luar negeri AS pada masa Trump lebih banyak digiring pada instrumen non-militer seperti pendekatan diplomatik dan ekonomi. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dipandang lebih efektif, efisien dari sisi anggaran, serta memiliki dampak yang lebih besar. Dalam kasus Rusia dan Ukraina misalnya, Trump terbilang sukses dalam melakukan pendekatan terhadap Putin dan Zelensky untuk memulai pembicaraan tentang gencatan senjata dan perdamaian, suatu hal yang sulit diinisiasi oleh pemerintahan AS pada zaman Joe Biden.
NAIKNYA Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) bukan saja berdampak pada meningkatnya ketegangan politik antarnegara, tapi pada cakupan yang lebih besar berpotensi mengubah struktur sistem internasional yang menjadi platform komunikasi dan relasi antar-aktor di level global. Perubahan struktur sistem internasional ini bukan tidak mungkin merupakan objektif by-design yang digagas oleh Trump dan ekosistem diplomatik AS, demi mendudukkan AS sebagai satu-satunya kekuatan utama dunia, mengungguli Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa baik dari sisi ekonomi maupun militer.
Naiknya Tiongkok sebagai rising power dunia dipandang AS sebagai sebuah kecolongan, alih-alih karena komitmen dan kapasitas Tiongkok sendiri. Kebijakan AS pada masa lalu, yang mengobarkan perang global melawan terorisme dengan menduduki Afghanistan dan Irak, selama dua puluh tahun lebih terhitung sejak 2001, telah menimbulkan konsekuensi pelemahan bahkan hilangnya pengaruh AS di level global. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah AS dipaksa untuk mengeluarkan banyak uang demi membiayai perang, membangun pemerintahan ala AS di kedua negara tersebut yang akhirnya berujung kegagalan, dan mau tidak mau mengurangi atensinya pada wilayah- wilayah konvensional yang menjadi medan pengaruh AS seperti Indo Pasifik, Timur Tengah, dan Asia Timur. Celah ini sukses dimanfaatkan Tiongkok dengan membangun kekuatan ekonomi dan militernya sepanjang berkurangnya pengaruh AS di kawasan.
Trump yang memiliki latar belakang yang kuat di bidang ekonomi, sebagai kepala negara menyadari bahwa mereposisi struktur sistem internasional melalui kekuatan militer, tidak akan berjalan efektif dan berpeluang mengulangi kesalahan yang sama di Afghanistan dan Irak. Penggunaan kekuatan militer juga tidak sesuai dengan jiwa zaman yang sudah meninggalkan konflik terbuka apalagi perang. Oleh sebab itu, corak politik dan kebijakan luar negeri AS pada masa Trump lebih banyak digiring pada instrumen non-militer seperti pendekatan diplomatik dan ekonomi. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dipandang lebih efektif, efisien dari sisi anggaran, serta memiliki dampak yang lebih besar. Dalam kasus Rusia dan Ukraina misalnya, Trump terbilang sukses dalam melakukan pendekatan terhadap Putin dan Zelensky untuk memulai pembicaraan tentang gencatan senjata dan perdamaian, suatu hal yang sulit diinisiasi oleh pemerintahan AS pada zaman Joe Biden.
Rivalitas AS-Tiongkok
Ambisi Trump, untuk tidak menyebut ambisi AS, untuk menguasai dunia dan mendudukkan kembali AS sebagai the one and only superpower dunia, dirumuskan secara cermat dan teliti. Dengan mengedepankan pendekatan manajemen risiko dan efektivitas efisiensi kebijakan, instrumen perang dagang digunakan untuk menekan negara-negara lain, agar tunduk dan berada di bawah subordinasi AS. Intensi AS dalam menekan negara-negara tersebut disinyalir kuat sebagai upaya AS, untuk mengajak komunitas dunia agar bersama-bersama memberikan tekanan kepada Tiongkok yang notabene merupakan rival berat AS di ranah perekonomian dunia. Ini tentunya bukan asumsi melainkan intensi empirik, jika menilik kebijakan yang diambil oleh AS. AS menerapkan tarif impor sebesar 125 persen untuk Tiongkok, sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagai perbandingan, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap Indonesia berada di angka 47 persen. Pun ketika AS mengambil kebijakan penangguhan pemberlakuan tarif impor dan membuka ruang negosiasi dengan negara-negara lain, yang merasa terbebani atas kebijakan yang diambil, AS justru tidak menerapkan hal yang serupa terhadap Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa AS benar-benar berupaya mengambil titik kulminasi dari rivalitas yang dilakukan dengan Tiongkok.
Dalam konteks rivalitas dengan Tiongkok, sembari melancarkan tekanan keras di bidang ekonomi, AS juga melancarkan strategi decoupling terhadap Tiongkok, untuk mengesankan Tiongkok di dunia internasional sebagai entitas pelanggar hak asasi manusia terhadap warga negaranya, serta aktor negara yang melakukan pelanggaran kaidah hukum internasional. Strategi decoupling atau menjatuhkan negara lain dengan berbagai instrumen ini, merujuk pada aksi-aksi Pemerintah Tiongkok yang melakukan kekerasan atas nama negara terhadap etnis minoritas Muslim di wilayah Xinjiang, aksi represif terhadap warga negara Taiwan dan Hongkong yang menyerukan pemisahan diri, serta aksi koersif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, yang menggunakan klaim tradisional untuk menegasikan keberlakukan hukum laut internasional UNCLOS 1982 demi menguasai wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di lautan tersebut. Strategi decoupling efektif untuk mendiskreditkan Tiongkok di forum-forum global sekelas PBB, tapi belum cukup untuk meruntuhkan kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan adidaya baru dunia.
Upaya AS untuk mereposisi struktur sistem internasional dan “menyingkirkan” Tiongkok dalam rivalitas global, akan direspons oleh Tiongkok. Tiongkok yang perlahan tapi pasti, membangun aliansi global dan proksi-proksi politik ekonomi melalui kerja sama strategis Shanghai Cooperation Organization (SCO) bersama Rusia di wilayah Asia Tengah, demi menguasai sumber daya ekonomi dan energi, serta soliditas kemitraan yang semakin kuat dalam kelompok BRICS plus, akan melakukan segala daya upaya untuk menjaga keberlangsungan pengaruhnya di kawasan Indo Pasifik yang saat ini bernilai paling strategis. Pertama, Tiongkok akan memastikan bahwa Rusia tetap menjadi mitra strategis di bidang politik dan militer di tengah rencana Trump dalam memediasi konflik Rusia dan Ukraina. Kedua, Tiongkok akan membalas strategi decoupling AS dengan menempuh langkah serupa seperti yang ditunjukkan dalam dukungan yang diberikan terhadap Palestina dan penolakan terhadap Israel yang dibekingi oleh AS. Ketiga, Tiongkok akan merapatkan barisan negara-negara Selatan, untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan ekonomi negara-negara Selatan, melalui peningkatan neraca perdagangan intra-organisasi, perluasan pasar produk di negara-negara berkembang, memberikan pinjaman ekonomi berbunga lunak terhadap negara-negara di kawasan Afrika, termasuk potensi untuk mengembangkan mata uang sendiri yang terlepas dari dependensi terhadap mata uang arus utama yang dikuasai oleh Barat.
Sikap Indonesia
Indonesia perlu mencermati secara serius upaya AS dalam mereposisi sistem internasional dari multipolar menjadi unipolar dengan AS sebagai penjuru. Upaya AS sangat berbahaya dan berpotensi mempengaruhi kedaulatan dan kepentingan nasional. Terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan AS, pemerintah Indonesia sudah seharusnya tidak bersikap reaktif-reaksioner apalagi menggadaikan kedaulatan nasional. Kebijakan perang tarif yang dilakukan oleh AS tidak menyasar Indonesia semata, melainkan hampir seluruh negara di dunia. Artinya, Indonesia perlu bersikap cermat dan wait and see terhadap reaksi komunitas global. Terlebih lagi AS membuka ruang negosiasi, yang artinya AS akan menerapkan politik akomodasi terhadap negara-negara yang terdampak dari kebijakan tersebut. Indonesia seyogianya tidak terseret oleh arus kepentingan yang dikobarkan AS, begitu juga dengan rivalitas yang dilakukan AS dengan Tiongkok. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memperkuat kemandirian ekonomi nasional, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki. Demikian pula halnya dalam panggung diplomasi internasional, sistem internasional yang bersifat multipolar harus dijaga keberlangsungannya, karena bipolaritas apalagi unipolaritas hanya menimbulkan dependensi dari satu dua kekuatan terhadap negara-negara lain, yang artinya merupakan ancaman nyata terhadap perdamaian dunia dan keadilan global. **
Boy Anugerah
Pengamat Hubungan Internasional

 ---
---